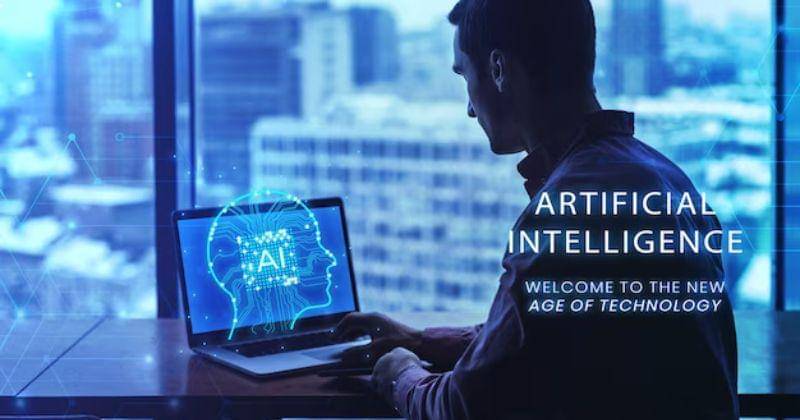Sejarah Perang Diponegoro, Perjuangan Melawan Kolonialisme Belanda

Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825-1830 adalah salah satu perlawanan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia melawan kolonialisme Belanda.
Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan Yogyakarta yang ingin membebaskan tanah Jawa dari cengkeraman penjajah.
Pangeran Diponegoro, yang lahir dengan nama Raden Mas Mustahar pada 11 November 1785, adalah putra Sultan Hamengkubuwono III dari selir bernama Raden Ajeng Mangkarawati.
Meskipun bukan putra mahkota, Diponegoro memiliki kedudukan yang terhormat di istana dan mendapat pendidikan yang baik dalam bidang agama Islam, sastra Jawa, dan ilmu kemiliteran, sehingga dirinya adalah sosok yang sesuai untuk memimpin perang besar ini.
Konflik ini berlangsung selama lima tahun dan melibatkan hampir seluruh wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Perang Diponegoro juga menjadi salah satu inspirasi kuat, yang berhasil memengaruhi gerakan perlawanan lain di berbagai daerah lain di Nusantara.
Meskipun pada akhirnya Diponegoro tertangkap, semangat perlawanannya tetap menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Berikut telah Popmama.com rangkum informasi seputar sejarah Perang Diponegoro.
1. Penyebab Perang Diponegoro
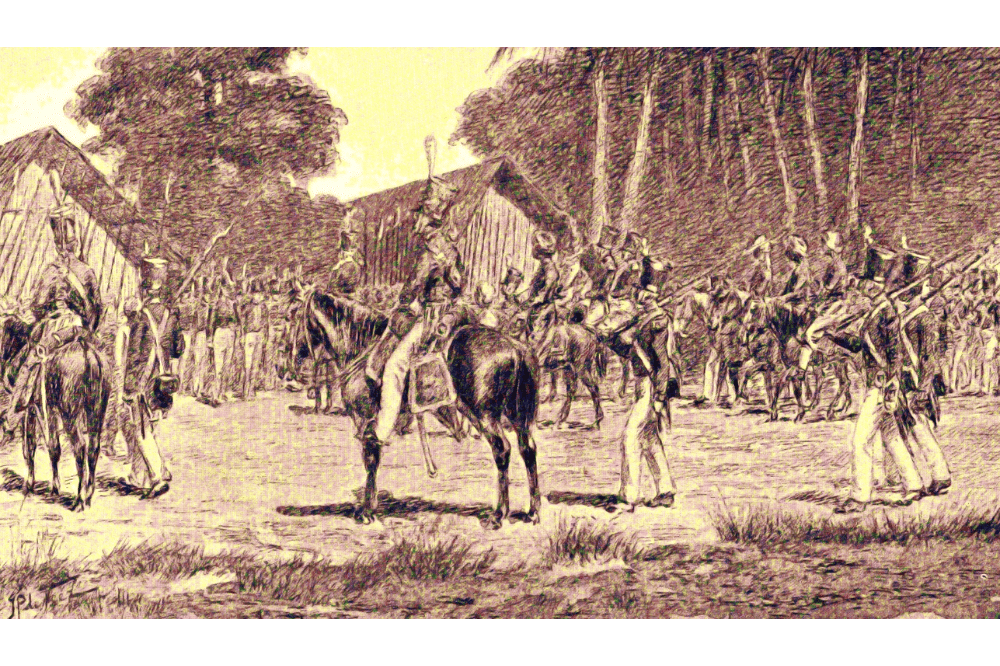
Perang Diponegoro tidak terjadi secara tiba-tiba. Perang ini terjadi karena akumulasi dari berbagai ketegangan yang telah lama mengendap antara kerajaan Yogyakarta dan pemerintah kolonial Belanda.
Salah satu penyebab utama adalah kebijakan Belanda yang semakin mengintervensi atau ikut campur dengan urusan internal kerajaan, terutama setelah Perang Napoleon berakhir dan Belanda kembali menguasai Hindia Belanda.
Sistem sewa tanah yang diperkenalkan Belanda memberatkan rakyat dan mengurangi kewenangan para bangsawan tradisional.
Selain itu, pembangunan jalan raya yang melewati tanah milik Diponegoro tanpa izin dan kompensasi yang layak menjadi pemicu langsung kemarahan sang pangeran.
Kondisi ekonomi yang memburuk akibat eksploitasi kolonial dan ketidakpuasan terhadap pemimpin daerah yang ditunjuk Belanda semakin memperparah situasi, menciptakan atmosfer yang siap meledak menjadi pemberontakan besar-besaran.
2. Fase awal perang (1825-1827)
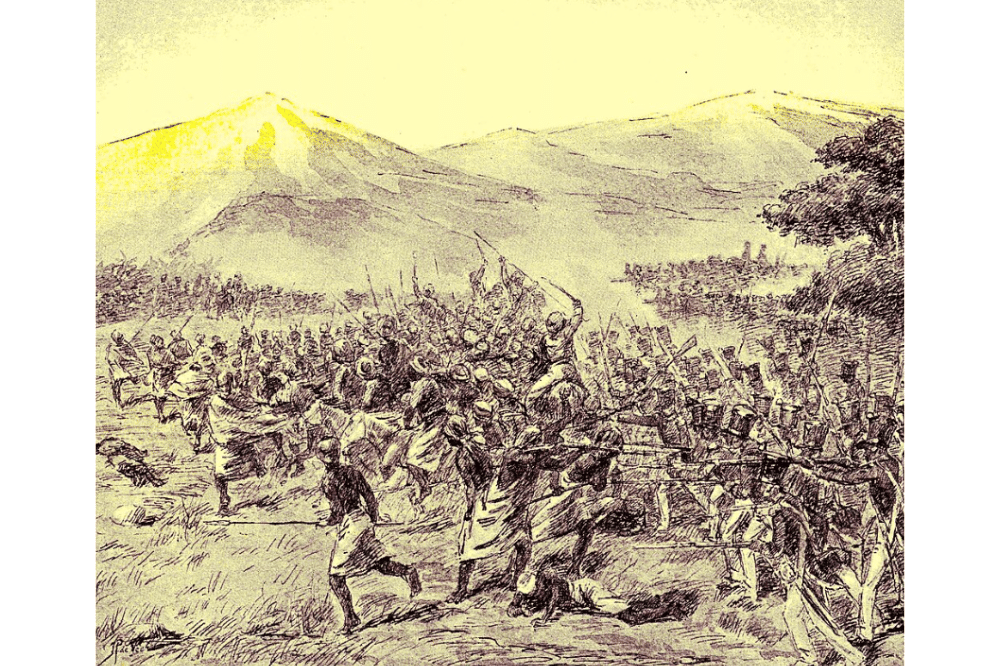
Pada Agustus 1825, pasukan Diponegoro berhasil merebut benteng Yogyakarta dan memaksa Sultan Hamengkubuwono V serta para pejabat Belanda mengungsi ke dalam benteng Vredeburg.
Dalam periode September-Oktober 1825, hampir seluruh wilayah Keresidenan Yogyakarta, kecuali kota Yogyakarta dan beberapa pos militer, jatuh ke tangan pasukan Diponegoro.
Ekspansi wilayah berlanjut ke timur hingga mencapai sebagian wilayah Keresidenan Surakarta, ke utara hingga Magelang dan Temanggung, serta ke selatan hingga pantai Samudera Hindia.
Pada tahun 1826, pasukan Diponegoro di bawah komando Sentot Alibasyah Prawirodirjo berhasil merebut beberapa benteng penting seperti Benteng Klaten dan mengancam keamanan Surakarta.
Keberhasilan ini membuat pemerintah Hindia Belanda di Batavia mulai mengirim bala bantuan dari berbagai daerah.
Pada periode ini, Diponegoro juga mulai membentuk struktur pemerintahan alternatif dengan mengangkat para bupati di wilayah-wilayah yang telah dikuasainya.
Hal ini menunjukkan bahwa perlawanan ini juga menjadi upaya serius untuk membangun tatanan pemerintahan yang baru.
3. Perubahan strategi Belanda (1827-1829)

Menghadapi kekalahan beruntun dan kerugian yang sangat besar, pemerintah Hindia Belanda mulai mengubah strategi perangnya pada tahun 1827.
Jenderal Hendrik Merkus de Kock yang ditunjuk sebagai panglima tertinggi memperkenalkan sistem benteng bergerak atau mobile fortress dan taktik pagar betis, yakni benteng kecil yang saling berhubungan untuk membatasi ruang gerak pasukan Diponegoro.
Strategi ini disertai dengan kebijakan bumi hangus, di mana desa-desa yang diduga mendukung Diponegoro dihancurkan dan penduduknya dipindahkan ke daerah konsentrasi yang diawasi ketat.
Merespons perubahan strategi Belanda ini, Diponegoro dan para komandannya seperti Sentot Alibasyah Prawirodirjo, Kyai Mojo, dan Ali Basyah Sentot mengubah taktik perang mereka menjadi perang gerilya.
Pasukan Diponegoro mulai meninggalkan benteng-benteng tetap dan beralih ke gua-gua, hutan, dan daerah perbukitan yang sulit dijangkau.
Tahun 1828-1829 merupakan fase paling yang intens dari perang gerilya, di mana pasukan Diponegoro melakukan serangan-serangan mendadak terhadap pos-pos Belanda, konvoi logistik, dan patroli militer.
Pada periode ini juga terjadi beberapa perpecahan internal dalam pasukan Diponegoro, terutama setelah Sentot Alibasyah Prawirodirjo memutuskan untuk menyerah kepada Belanda pada tahun 1829.
4. Diplomasi menjelang akhir perang (1829-1830)

Memasuki tahun 1829, baik pihak Diponegoro maupun Belanda mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelah bertempur selama empat tahun.
Biaya perang yang sangat besar telah menguras kas kolonial Belanda hingga mencapai 20 juta gulden, sementara korban jiwa dari kedua belah pihak terus berjatuhan.
Kondisi ini membuka peluang untuk memulai jalur diplomasi. Pada awal tahun 1830, Jenderal De Kock mulai melakukan pendekatan diplomatik kepada Diponegoro melalui perantara para bangsawan Yogyakarta yang masih memiliki hubungan baik dengan kedua belah pihak.
Komunikasi awal dilakukan melalui surat-menyurat yang membahas kemungkinan gencatan senjata dan perundingan damai.
Diponegoro, yang pada saat itu juga menghadapi tekanan internal dari sebagian pengikutnya yang mulai lelah berperang, menunjukkan keterbukaan untuk melakukan negosiasi dengan syarat-syarat tertentu.
Ia menuntut pengakuan atas statusnya sebagai pelindung agama Islam di Jawa, otonomi wilayah tertentu, dan jaminan keselamatan bagi para pengikutnya.
Pemerintah Belanda, melalui De Kock, tampaknya memberikan sinyal positif terhadap tuntutan-tuntutan tersebut dan mengundang Diponegoro untuk melakukan perundingan langsung.
5. Akhir perang dan penangkapan Diponegoro (1830)

Akhir Perang Diponegoro terjadi dengan cara yang sangat kontroversial.
Pada tanggal 28 Maret 1830, atas undangan Jenderal De Kock, Diponegoro datang ke Magelang untuk menghadiri perundingan damai yang telah dijanjikan.
Dalam pertemuan tersebut, Diponegoro didampingi oleh beberapa pengikut setianya, termasuk putra-putranya.
Namun, ketika Diponegoro tiba di tempat perundingan dan mulai menyampaikan syarat-syaratnya untuk perdamaian, De Kock tiba-tiba menyatakan bahwa ia harus menerima pengasingan sebagai satu-satunya syarat perdamaian.
Ketika Diponegoro menolak dengan tegas, ia langsung ditangkap oleh pasukan Belanda yang telah disiapkan sebelumnya.
Penangkapan ini tentunya menjadi pelanggaran berat terhadap jaminan keamanan yang telah diberikan dan merupakan bentuk pengkhianatan diplomatik.
Setelah ditangkap, Diponegoro langsung diangkut ke Semarang dan kemudian diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara, pada bulan Mei 1830.
Penangkapan Pangeran Diponegoro sebagai pemimpin perang ini secara efektif mengakhiri perlawanan bersenjata, meskipun beberapa kelompok kecil pengikutnya masih melanjutkan perlawanan hingga beberapa bulan kemudian.
Dengan berakhirnya Perang Diponegoro, pemerintah Belanda berhasil memantapkan kontrolnya atas Jawa, namun dengan biaya yang sangat mahal dan metode licik yang mewarnai sejarah kolonial mereka.
Itulah informasi mengenai sejarah Perang Diponegoro, semoga dapat menambah wawasan, ya!