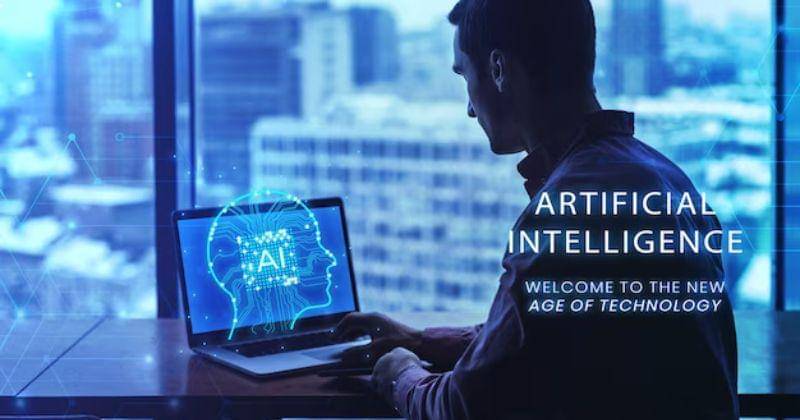Alasan Mengapa Remaja Menjauh dari Orangtua Menjelang Masa Adolesensya

Pernahkah Mama merasa bahwa semakin anak tumbuh besar, semakin mereka terasa menjauh dari pelukan dan perhatian kita?
Jangan khawatir, Ma, itu hal yang wajar terjadi menjelang masa adolesensnya.
Fase ini memang penuh pasang-surut, terutama dalam hubungan anak dan orangtua sendiri.
Ada banyak faktor yang memengaruhi perkembangan remaja selain pola asuh di rumah, seperti lingkungan sosial, karakter bawaan, pengaruh teman sebaya, pilihan pribadi, hingga faktor budaya.
Dalam artikel ini, Popmama.com akan membahas alasan mengapa anak remaja menjauh dari orangtua saat masa adolesens. Jika Mama mengalami problem yang sama, yuk cari tahu mengapa!
1. Pencarian kemandirian

Saat pubertas, perubahan hormon mendorong remaja untuk mencari identitas dan kemandirian. Ini membuat mereka mulai menjaga jarak dari orangtua dan lebih mengandalkan teman sebaya dalam mengambil keputusan.
Meski sering mengaku mendambakan kemandirian, kenyataannya remaja masih sangat terlibat dalam kehidupan di rumah. Keterikatan emosional dan ketidaksiapan dalam mengelola kehidupan sepenuhnya menjadikan mereka menunda keinginan tersebut, seolah sulit untuk benar-benar melepaskan diri.
Secara neurologis dan psikologis, keinginan remaja untuk mandiri dan mengurangi kontrol orangtua muncul lebih cepat dibanding kemampuan mereka mengatur diri sendiri. Ini terkait dengan ketidakseimbangan perkembangan otak: bagian sistem emosi (ventral affective system) tumbuh lebih cepat daripada prefrontal cortex, yang bertanggung jawab atas kontrol diri dan pengambilan keputusan.
Dampaknya, remaja mengalami dorongan untuk kebebasan tanpa dibarengi kemampuan berpikir jernih dan bijak. Saat orangtua mendorong agar remaja lebih bertanggung jawab, tetapi anak tetap ingin menghindari kontrol tanpa memiliki self-regulation yang cukup, konflik pun tak terhindarkan, dan hubungan pun bisa terasa renggang.
2. Perubahan perspektif

Selama masa pubertas, anak-anak mulai melihat orangtua bukan lagi sebagai pusat dunia sosial mereka. Mereka mulai membangun kehidupan sosial yang lebih luas dan beragam di luar lingkungan rumah.
Remaja cenderung menafsirkan kontrol orangtua secara berbeda tergantung pada ranah sosial mana yang orangtua ‘campuri’.
Misalnya, remaja cenderung merasakan bahwa ketika orangtua terlalu mengatur urusan pribadi mereka seperti emosi atau perasaan mereka, gaya berpakaian atau keputusan pribadi mereka, hal tersebut mungkin dianggap sebagai bentuk pengendalian yang berlebihan dan membuat mereka merasa terkekang secara psikologis.
Namun, ketika kontrol orangtua berkaitan dengan kehidupan sosial mereka, seperti pemilihan teman atau partisipasi dalam kegiatan di luar rumah, remaja pada umumnya lebih dapat menerima dan mengerti alasan orangtua tanpa merasa terlalu dikekang, karena mereka mengetahui alasan di baliknya
Kontrol orangtua yang menyentuh ranah personalnya dirasakan lebih sensitif dan berpengaruh besar terhadap perasaan remaja, sementara kontrol di ranah sosial biasanya lebih mudah diterima dan tidak menimbulkan perasaan terkekang. Tetapi, tentu kasus pada tiap anak berbeda-beda.
3. Reorganisasi Relasi

Branje dalam risetnya, Development of Parent–Adolescent Relationships: Conflict Interactions as a Mechanism of Change, menjelaskan bahwa hubungan orangtua dan anak pada masa kanak-kanak bersifat vertikal, yaitu ketika orangtua memegang kontrol, otoritas, dan dianggap lebih tahu segala hal.
Namun, saat memasuki masa adolesens, remaja mulai mengembangkan kapasitas kognitif dan emosional untuk berpikir abstrak, memahami relativitas nilai, dan memandang diri mereka sebagai individu otonom.
Inilah yang memicu dorongan ke arah relasi horizontal, yaitu relasi yang lebih setara dan timbal balik, yaitu ketika orangtua dan anak memiliki opini yang setara, dapat memberi masukan satu sama lain. Tapi, perubahan ini tidak selalu terjadi tanpa konflik.
Kedua belah pihak, baik anak atau orangtua, akan memerlukan waktu untuk memprosesnya.
4. Respons orangtua terhadap perubahan

Cara orangtua merespons fase perkembangan remaja turut memengaruhi seberapa dekat atau jauhnya hubungan yang terjalin.
Misalnya, bentuk intimidasi dari orangtua seperti, “Aku menurut karena takut dimarahi” memang bisa membuat anak patuh, tetapi hanya karena dilandasi rasa takut. Di sisi lain, manipulasi emosional seperti misalnya, “Aku merasa bersalah karena membuat orangtuaku sedih” dapat membuat anak merasa bersalah atas emosi yang tidak ada dalam kontrolnya. Kedua pendekatan ini sebaiknya dihindari karena bisa merusak rasa aman dan kepercayaan dalam hubungan antara orangtua dan anak.
Remaja yang merasa terlalu dikontrol atau justru diabaikan cenderung menjaga jarak lebih jauh, baik sebagai bentuk perlindungan diri maupun protes terhadap sikap orangtua.
Namun sebenarnya, konflik-konflik yang muncul selama masa ini bisa menjadi kesempatan untuk menegosiasikan kembali peran dan batasan antara orangtua dan anak.
Pertengkaran atau ketegangan yang muncul dapat menjadi jalan untuk mengatur ulang hubungan agar lebih setara, ketika otonomi remaja dihargai dan keputusan diambil lebih banyak melalui dialog.
Ketika orangtua bersedia mengurangi kontrol berlebih dan bersikap lebih terbuka terhadap kebutuhan anak untuk mandiri, konflik biasanya akan berkurang. Hubungan pun bisa kembali hangat, bahkan lebih sehat dibanding sebelumnya.
Dengan kata lain, konflik yang terjadi selama masa remaja bukanlah tanda hubungan rusak, melainkan bagian penting dalam proses penyesuaian dan pertumbuhan hubungan yang lebih dewasa antara orangtua dan anak.
Ternyata ada banyak faktor ya, Ma, di balik alasan mengapa anak remaja menjauh dari orangtua saat masa adolesens. Tapi tidak apa-apa, Ma, ketahuilah bahwa anak remaja, sama seperti kita, kadang membutuhkan ruang mereka sendiri untuk menerima perubahan. Asalkan tetap selalu dipantau, ya!